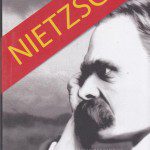| Judul | Nietzsche |
| Pengarang | St. Sunardi |
| Penerbit | LKiS |
| Tahun Terbit | 1996 |
| Tebal Halaman | 215 + xiv |
Tidak dapat dipungkiri, figur seorang Nietzsche “diperoleh” berpuluh-puluh tahun setelah kematiannya. Semasa hidup, pemikiran dan konsepsi filsafatnya tidak banyak dilirik oleh orang. Justru setelah kematiannya, filsafat Nietzsche menempati ruang-ruang di mana kemapanan bercokol kemudian didobrak oleh (konon) Nietzcshean. Bagaimanapun juga, ia adalah filsuf penting yang berada di garis demarkrasi periodisasi sejarah filsafat: antara filsafat modern dan kontemporer (post-modern). Dan pengaruhnya begitu luas. Katakanlah filsuf sekaliber Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jacques Derrida, dan Muhammad Iqbal. Beberapa inti pemikiran mereka terpengaruh oleh filsafat Nietzsche (ST. Sunardi, 1999: 119-120).
Bagi beberapa kalangan, filsafat Nietzsche tidak mendapat tempat. Karena ia sendiri adalah filsuf yang anti mainstream. Selain cara menuangkan gagasan filosofisnya dalam wadah aforisme -aforisme puitis-sangat berbeda dengan filsuf-filsuf sebelumnya yang cenderung menggunakan tulisan sistematis ilmiah- yang menyulitkan pembaca. Pemikirannya juga jauh dari kebiasaan-kebiasaan umum pada waktu itu. Bahkan ia “mengoyak-ngoyak” segala kemapanan yang berlaku. Ditambah gaya tulisannya yang sinis dan terkadang berbau sarkas serta atribut ateis pada dirinya. Sebagaimana ateismenya memuncak saat ia dengan lantang berkata: “Tuhan sudah mati, dan kita semua adalah pembunuhnya.”
Gaya aforistik demikian dipilih oleh Nietzsche untuk mengungkapkan gagasan-gagasan karena dinilai tepat. Mengingat usaha yang dilakukannya, secara garis besar, merupakan hal-hal yang baru dan tidak mau terikat dengan gagasan terdahulu. Gagasan yang luas, oleh Nietzsche, justru dirasa akan dipersempit oleh gaya kepenulisan sistematis-ilmiah. Di samping itu, ia juga berjiwa ‘seniman’ yang (konon) diwarisi oleh Richard Wagner, musikus sekaligus penyair.
Nietzsche tidak pernah mau untuk diikuti. Jika pengikut Hegel mengatasnamakan diri sebagai Hegelian, Marxis untuk pengikut Karl Marx, dan pengikut Descartes bernama Cartesian. Maka pengikut Nietzsche tidak bernama (anonim). Jika akhir-akhir ini kita kenal nietzschean, nietzcholog, dan nietzchemania, itu semata-mata kehendak personal atau golongan untuk “melegitimasi” apa yang mereka lakukan (pikirkan). Hal ini berhubungan sekali dengan kondisi kehidupan Nietzsche yang penuh dengan: kesendirian, kegelisahan, dan kesakitan serta berujung pada ‘gila’. Ia tidak menginginkan “pengikutnya” merasakan kenestapan hidup sebagaimana ia rasakan. Bagi Nietzsche, untuk menyelami pemikirannya harus dengan menyelam di lautan “diri sendiri”. Julukan paling setia untuk pengikutnya adalah “diri sendiri.” Semacam menjawab atas pernyataan fenomenal Socrates: gnothi seauton.
Untuk memperbincangkan Nietzsche, kali ini saya menghadirkan sebuah buku yang saya kira cukup representatif atas pokok-pokok pemikiran Nietzsche. Buku berjudul Nietzsche karya ST. Sunardi. Tidak lagi dalam serpihan-serpihan aforistik. ST Sunardi telah menuliskannya sedemikian rupa: sistematis-ilmiah, sehingga mudah untuk dipahami.
Nihilisme dan Kematian Tuhan
Nihilisme dan kematian Tuhan adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Untuk itu, marilah kita mulai satu per satu, kemudian mempertautkan keduanya sebagai suatu keutuhan yang berbeda. Kita mulai dengan nihilisme. St. Sunardi melalui buku ini mengartikan nihilisme sebagai runtuhnya seluruh nilai dan makna meliputi seluruh bidang kehidupan (bidang keagamaan dan ilmu pengetahuan) (St. Sunardi, 1999: 22)
Keruntuhan nilai dan makna itu disebabkan oleh tindak-tanduk manusia di dunia. Secara kronologis, dahulu manusia beragama dan secara otomatis ber-Tuhan. Tuhan, yang adi-kodrati (other world), adalah kepastian absolut. Berikut nilai dan maknanya. Keadaan seperti ini memang secara historis adalah bentuk ketidakberdayaan dan ketergantungan manusia. Kita lihat bagaimana moral Kristen yang absolut “membelenggu” manusia.
Ada empat ‘fungsi’ moral Kristen. Pertama, sebagai jaminan manusia yang merasa kecil dan tidak pasti. Kedua, sebagai perintah-perintah Tuhan di dunia. Ketiga, sebagai pengetahuan nilai-nilai absolut untuk memahami apa yang paling penting. Keempat, sebagai sarana pemeliharaan bagi manusia. Keempat ‘fungsi’ moral Kristen, menurut St. Sunardi, membuat manusia menjadi sedemikian pasti dan aman akan hidupnya, sehingga sulit melepaskannya (St. Sunardi, 1999: 30).
Lambat laun, keabsolutan moral Kristen (moral agama secara umum) tersebut, akan “tersaingi” oleh manusia dan atau ilmu pengetahuan yang juga mengalami perkembangan. Sehingga, manusia “mensejajarkan” –untuk tidak mengatakan “menuhankan”– diri dengan Tuhan. Dengan kata lain, manusia dan atau ilmu pengetahuan “mengabsolutkan” diri. Bahwa kepastian sesungguhnya adalah Aku. Tuhan-tuhan kecil bermunculan.
Dengan paham ateisme yang dianut Nietzsche, untuk menanggapi keadaan manusia yang “tergantung”, ia mewartakan kematian Tuhan dan tuhan-tuhan: “Gott ist tot! Gott bleibt tot! Und wir haben ihn getotet! (Tuhan sudah mati! Tuhan terus mati! Kita telah membunuhnya). Bahkan ia “mendoakan” kematian Tuhan: Requiem aeternam deo! (semoga Tuhan beristirahat dalam kedamaian abadi).
Dengan kematian Tuhan, kata Nietzsche, semua makna dan nilai yang mencirikan “kewarasan” telah roboh (St. Sunardi, 1999: 26). Keadaan seperti ini yang ia maksud nihilisme. Keadaan saat nilai dan makna (dan segala jaminan-jaminan Tuhan) telah runtuh, sementara nilai-nilai baru belum ada. Oleh karena itu, lanjut Nietzsche, tugas manusia selanjutnya adalah mengatasi nihilisme tanpa harus menolaknya. Karena mau tidak mau, menolak atau menerima, nihilisme adalah keniscayaan.
Mengatasi nihilisme tidak dengan diam atau netral. Sikap seperti ini, dalam buku ini, disebut nihilisme pasif, yaitu sikap saat manusia telah mengafirmasi runtuhnya makna dan nilai, tetapi Ia belum bisa meninggalkan (atau kehilangan) “romantisme” nilai dan makna terdahulu. Sikap yang seharusnya diambil adalah melakukan ‘pembalikan nilai-nilai’, yang kemudian disebut nihilisme aktif.
‘Pembalikan nilai-nilai’ di sini adalah mempertanyakan selalu tiada henti nilai dan makna yang sudah ada. Sebagaimana yang ditulis St. Sunardi di dalam buku ini, Nietzsche bermaksud mengadakan penilaian kembali seluruh “nilai-nilai” yang sudah ada sampai sekarang, yang cenderung memfosil sampai sekarang. Dengan kata lain, Nietzsche menginginkan tidak adanya “nilai-nilai” dan kebenaran absolut, yang manusia dijamin olehnya (atau -Nya). Karena ia beranggapan bahwa segala sesuatu itu khaos dan manusia harus bebas dari segala makna absolut yang menjamin dirinya dan dunianya.
Ketika “nilai-nilai” itu sudah (akan) menjadi absolut, maka manusia harus meninggalkannya. Seperti yang tertuang dalam satu bagian aforisme Nitzsche berjudul Im Horizont des Unendlichen (Dalam Horison Ketidakterbatasan). Bahwa, St. Sunardi memaparkan, Nietzsche tidak mau mencari pulau atau daratan yang dapat dipakai sebagai tempat tinggal yang aman. Dia mau mencari sampan kecil untuk mengarungi samudera raya supaya dapat menikmati ketakterbatasan dan geloranya. St. Sunardi melanjutkan: kalau sampan kita sudah aus dan tak dapat digunakan berlayar lagi, sampan itu harus dihancurkan dan diganti dengan sampan baru (St. Sunardi, 1999: 32-33).
Segala Sesuatu dalam ‘Genggaman’ Kehendak Untuk Berkuasa
Gagasan Nietzsche tentang kehendak untuk berkuasa (Will to Power) adalah melanjutkan (baca: mengkongkretkan dengan makna lain) gagasan sebelumnya, nihilisme. Kehendak untuk berkuasa, sebagaimana dipahami antek-antek Nazi (semisal Alferd Bäumler dan adiknya, Elisabeth), bukanlah provokasi politik. Hal ini didasarkan atas gaya hidup Nietzsche (yang juga menjadi latar belakang pemikirannya) yang menyukai kesendirian dan kesunyian (individualisme dan eksistensialisme). Selain itu, ia menaruh perasaan ‘benci’ terhadap segala sesuatu yang dilembagakan laiknya negara. Karena negara bertentangan dengan naluriah manusia berupa kebebasan untuk merealisasikan diri. Sehingga, St. Sunardi di dalam buku ini, memberi kesimpulan bahwa: kehendak untuk berkuasa bukanlah suatu provokasi politik.
Lantas apa yang dimaksud kehendak untuk berkuasa? Jawaban atas pertanyaan ini dapat kita temukan secara terpisah dalam beberapa karya Nietzsche. Sebagaimana juga dikutip dalam buku ini. Pertama, dalam buku Beyond Good and Evil, kehendak untuk berkuasa adalah hakekat dunia. Kedua, dalam buku The Genealogy of Morals bahwa hakekat hidup adalah kehendak untuk berkuasa. Dan ketiga, dalam The Will to Power, ia menyebutkan bahwa hakekat terdalam dari ada (being) adalah kehendak untuk berkuasa. Dengan demikian, kehendak untuk berkuasa adalah hakekat dari segala-galanya: dunia, hidup, dan ada (being).
Lebih lanjut, Nietzsche menampik anggapan bahwa kehendak untuk berkuasa adalah substansi dari segala sesuatu laiknya pemahaman para metafisis. Ia dengan lantang mengatakan bahwa: kehendak untuk berkuasa merupakan khaos yang tak mempunyai landasan apapun. Dan khaos ini berada di bawah segala dasar seperti dibayangkan kaum metafisis (St. Sunardi, 1999: 42).
Secara etimologis, kehendak untuk berkuasa tersusun dari kata dasar ‘kehendak’ (will) dan ‘kuasa’ atau ‘kekuatan’ (power). ‘Kehendak’ diartikan sebagai gejala yang sifatnya plural, yang muncul karena terjadinya perbedaan ‘kekuatan’ (power). ‘Kehendak’ bukanlah substansial-metafisik. Munculnya perbedaan disebabkan oleh sifat alamiah power yang selalu merasa ‘lebih kuat’ dari dirinya sendiri, mengatasi dirinya sendiri dan pastinya berbeda dengan identitas diri (St. Sunardi, 1999: 42)
Dari menelaah kata per kata di atas, St. Sunardi menyimpulkan bahwa kehendak untuk berkuasa merupakan hakekat dari segala sesuatu (dunia, hidup, dan ada (being)), yang berarti: dasar dari segala sesuatu merupakan dinamisme yang masih berada dalam status khaos. Atau meminjam perkataan Nietzsche dalam salah satu bagian aforismenya: Dunia, hidup, dan ada seolah-olah terapung di atas gelora samudera, dan bukannya tertancap pada suatu benua atau daratan.
Demikian pula yang berlaku dalam pengetahuan. Nietzsche melakukan kritik terhadap pengetahun yang selama ini bersifat dogmatis dan taklid. Dan pengetahuan seperti itu dianggap benar oleh manusia yang justru membahayakan diri manusia itu sendiri. Tentang kritik atas pengetahuan, hal ini senada dengan teori yang dikembangkan Karl Popper tentang (1) the thesis of refutability dan (2) the principle of falsification. Bahwa (1) suatu ucapan atau hipotesa bersifat ilmiah, kalau secara prinsipal terdapat kemungkinan untuk menyangkalnya, dan (2) suatu teori atau ucapan bersifat ilmiah, jika terdapat kemungkinan untuk menyatakan salah.
Bagi Nietzsche, pengetahuan bukanlah jalan untuk mengantarkan manusia kepada kebenaran mutlak yang dengannya manusia berlindung. Pengetahuan semata-mata untuk menguasai keadaan. Seperti diungkapkan diawal, Nietzsche sangat benci terhadap ‘kemutlakan’, ‘keabsolutan’, dan kosmos. Kebenaran yang ia maksud adalah kekeliruan yang untuk sementara waktu dianggap benar, meskipun itu sebenarnya merupakan kekeliruan. (St. Sunardi, 1999: 67). Lebih jauh lagi, kebenaran merupakan bentuk hubungan dari beberapa kekeliruan. Dari gagasan ini (kehendak untuk berkuasa), muncullah paham perspektivisme Nietzsche tentang kebenaran.
Dari Zarathustra, ‘Keluar’ Übermensch dan Kembalinya Segala Sesuatu
Zarathustra adalah tokoh utama dalam buku Nietzsche berjudul Thus Spoke Zarathustra. Ia mewartakan tentang kedatangan manusia super Übermensch dan Kembalinya Segala Sesuatu (Marc Sautet, 2001: 128-135).
Mari kita terlebih dahulu memahami tentang Übermensch. Jika kehendak untuk berkuasa merupakan tatanan moralitas naturalistik ala Nietzsche, maka Übermensch adalah tujuan hidupnya. Melalui Übermensch, Nietzsche ingin mengajak manusia untuk menikmati kehidupan yang tak ada arah. Seperti ungkapannya yang juga terkandung dalam buku ini: “Lihatlah, aku mengajarkan Übermensch kepadamu! Übermensch adalah makna dunia ini. Biarkanlah kehendakmu berseru: Hendaknya Übermensch menjadi makna dunia ini!”
Kemudian kita bertanya apa yang dimaksud Übermensch? Terdiri dari dua kata: über- artinya ‘di atas’ dan Mensch artinya ‘manusia’. Di dalam bahasa Indonesia, Übermensch seringkali diterjemahkan menjadi: ‘Manusia Atas’ atau ‘Manusia Unggul’ (St. Sunardi, 1999: 94-95).
Tentang arti sebenarnya, Nietzsche mengatakan bahwa Übermensch adalah makna dari dunia ini. Warisan ‘nilai dan makna’ dari kebudayaan telah runtuh, ditambah ‘kematian Tuhan’ yang menciptakan Horizon Ketidakterbatasan, maka perlu adanya ‘nilai dan makna’ untuk memenuhi kebutuhan manusia. ‘Nilai dan makna’ itulah Übermensch yang mengajarkan nilai tanpa jaminan dan membuat orang ‘kecanduan’. Dengan kata lain, Übermensch adalah cara manusia memberi nilai pada dirinya sendiri (St. Sunardi, 1999: 97).
Sebagai pembanding, St. Sunardi dalam buku ini juga memaparkan tentang pengertian Übermensch yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Ada yang mengartikan Übermensch sebagai kualitas personal yang pada suatu saat nanti nyata ada laiknya konsepsi tentang Ratu Adil atau Mesias. Ada juga yang menafsirkan Übermensch adalah ‘manusia kuat’ yang akan menghancurkan segala sesuatu yang menghambat dirinya. Penafsiran terakhir dalam buku ini dilakukan oleh Elizabeth, adik kandung Nietzsche, yang mengatakan bahwa: Übermensch sudah ada dalam diri Adolf Hitler.
Semua penafsiran di atas tidak sesuai dengan arti Übermensch. Sebagaimana di atas telah diutarakan bahwa Übermensch adalah tujuan dari segala bentuk tindakan moral (kehendak untuk berkuasa). Maka, buku ini berkesimpulan: Übermensch adalah kemungkinan terbesar yang bisa dilihat dan dapat dicapai seseorang berdasarkan prinsip kehendak untuk berkuasa. Übermensch selalu berada di depan mata setiap orang yang berkehendak untuk berkuasa. Dengan demikian, Übermensch tidak akan pernah ditunjuk dalam perjalanan sejarah (St. Sunardi, 1999: 105).
Warta kedua yang keluar dari mulut Zarathustra adalah kembalinya segala sesuatu atau dalam bahasa Jerman dan Inggrisnya: die ewige Wiederkehr des Gleichen, the eternal recurence of the same. Gagasan tentang kembalinya segala sesuatu adalah gagasan pamungkas guna ‘memantapkan’ gagasan-gagasan sebelumnya: kehendak untuk berkuasa dan Übermensch. Di sini, Nietzsche mengambil sikap afirmatif akan hidup. Yaitu sikap, yang menurut saya, lebih “mengateiskan” diri. Kenapa begitu? Mari kita lihat ulasan selanjutnya dalam tulisan ini.
Kembalinya segala sesuatu, bagi Nietzsche, adalah pengafirmasian dunia secara mutlak. Segala sesuatu yang ada dan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengulangan dirinya sendiri. Pengulangan tersebut secara otomatis menegasikan keberadaan penciptaan dan pelenyapan. Dengan kata lain, dunia ini bersifat kekal, maka tidak ada awal dan akhir dari dunia. Semua yang terjadi mengikuti prinsip pengulangan: kembalinya segala sesuatu. Sementara kesimpulan yang mengatakan bahwa dunia itu diciptakaan, hal ini, bagi Nietzsche, semata-mata kesimpulan logika dan teologis belaka. Untuk memperjelas, saya mengutip catatan Nietzsche dalam buku ini (St. Sunardi, 1999: 113):
“Dunia ini ada; dunia bukan merupakan sesuatu yang menjadi, bukan sesuatu yang berjalan. Atau dapat juga dikatakan demikian: dunia ini menjadi, dunia ini berjalan, tetapi tidak pernah mempunyai permulaan untuk menjadi dan tidak pernah berhenti berjalan. Dunia mempertahankan dirinya dengan dua cara itu. Dunia hidup berdasarkan dirinya sendiri –sisa-sisa tubuhnya menjadi maknanya.”
Jalan pembuktian yang dimajukan Nietzsche adalah keberadaan dunia yang merupakan energi raksasa. Energi, seperti pengertian umum, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak berkembang dan menyusut, serta mustahil ada perubahan terhadapnya. Dunia, masih dalam bahasan ini, mempunyai pusat-pusat energi. Antara satu sama lain mengalami proses kombinasi-kombinasi. Sehingga terjadi pemenuhan satu sama lain yang pada waktu tertentu dapat terpenuhi. Jika kombinasi-kombinasi sudah terpenuhi, maka akan terjadi pengulangan secara terus menerus. Demikianlah dunia ini ada: semua yang pernah terjadi dan ada akan terulang lagi secara abadi (in infinitum) (St. Sunardi, 1999: 117).
Penutup: Kebencian akan Finalitas
Sebagai penutup dari ulasan buku Nietzsche karya St. Sunardi ini, saya bermaksud menghadirkan sepatah dua patah kata dari A. Setyo Wibowo dalam pendahuluan bukunya: Gaya Filsafat Nietzsche. Secara garis besar (meskipun tidak seluruhnya), filsafat Nietzsche bergerak pada pertentangan antara idée fixe (ide yang fiksatif, ide final, yang terakhir) dan idée fluxe (ide menjadi). Dengan berpegang teguh pada idée fluxe, Nietzsche melakukan kritik terhadap idée fixe yang dianggapnya sebagai sebuah ‘kesempurnaan’, ‘kemutlakan’ dan ‘keabsolutan’. Dan ujung-ujungnya adalah menindas, memperkosa, dan menghakimi manusia dengan jaminan-jaminan ‘keilahian’.
Ulasan buku ini adalah sebuah pengantar (paling) awal tentang pemikiran Nietzsche, yang oleh beberapa kalangan sulit dipahami. Saya kira, buku karya St. Sunardi ini sangat representatif untuk dijadikan modal awal menuju pemahaman akan gagasan dan pemikiran Nietzsche. Last, but not least, tulisan ini –meminjam perkataan Nietzsche– merupakan kumpulan dari ‘kekeliruan’ yang untuk sementara waktu dibenarkan. (Melfin Zaenuri, Mahasiswa Filsafat UGM 14′).
Daftar Rujukan
Sautet, Marc. 2001. Nietzsche Untuk Pemula. [penj. Imelda Kusumastuty]. Yoyakarta: Kanisius.
Sunardi, St. 1999. Nietzsche. Yogyakarta: LkiS.